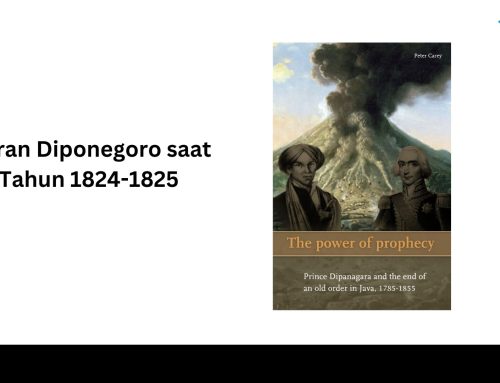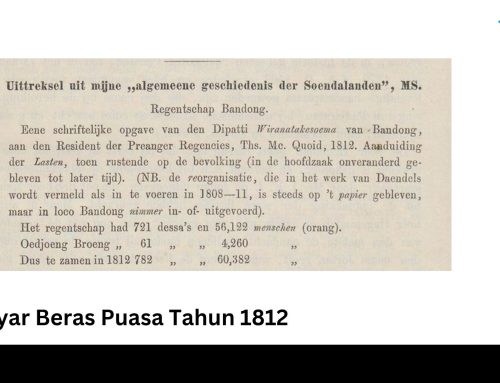Hal yang seru dari baca buku adalah tidak seorangpun yang bisa mencuri ilmunya darimu, kecuali engkau membaginya. Dan sebaik-baik ilmu adalah yang dibagikan
Kurang lebih 16 tahun lalu, ketika duduk di bangku kelas II SD, saya mempunyai sebuah buku favorit dengan ilustrasi penuh warna berjudul ‘Jack dan Kacang Buncis’. Buku itu bukan milik saya dan entah milik siapa. Sebab, buku itu tergeletak begitu saja di laci meja kelas, selama berbulan-bulan. Kenapa saya tahu sampai berbulan-bulan lamanya? Sebab, setiap hari ketika istirahat kedua, sejak saya menemukan buku itu di laci meja, saya selalu menyempatkan diri membacanya. Berulang-ulang. Tanpa bosan. Mengapa di jam istirahat kedua? Karena uang saku saya yang hanya Rp. 200,- pasti sudah habis. Jadi, pada waktu itulah, saya isi waktu dengan membaca buku. Saya sampai hapal isi cerita dalam buku itu di luar kepala.
Cerita di atas adalah fragmen kecil awal-mula saya berkenalan dengan buku. Bagi saya, seorang anak yang lahir dari keluarga yang sangat biasa-biasa saja, buku merupakan salah satu benda mewah. Bagi keluarga saya, buku selalu identik dengan sekolah. Jika guru tidak memerintah untuk membeli sebuah buku, maka kita tidak perlu memilikinya. “Buku kuwe larang. Tuku sing kanggo nggo sekolah bae. Duite aja diubah-ubah,” kata simbah. Artinya, “Buku itu harganya mahal. Beli yang terpakai saja untuk sekolah. Jangan buang-buang uang!”
Besar di Lingkungan Tanpa Akses Buku
Sejak berusia dua bulan, saya dibesarkan oleh kakek dan nenek yang saya panggil simbah. Beliau berdua, yang lahir di era penjajahan Jepang, tidak pernah mengenyam bangku pendidikan. Simbah puteri bisa membaca karena belajar di balai desa ketika pemerintah mengeluarkan program Indonesia bebas buta aksara.
Beliau berdua tidak pernah dengan sengaja menyuruh saya belajar. Tapi, kalau saya tidak mengaji, simbah bisa marah besar. Jadilah saya tumbuh sebagai bocah yang tidak gemar belajar apalagi membaca. Tapi rajin mengaji. Sepulang sekolah sampai menjelang Maghrib agenda harian saya adalah main di kebun, di sawah, atau di kali (sungai) bersama teman-teman. Kami bocah-bocah desa yang tidak kenal tidur siang. Apalagi membaca dongeng. Sejak Maghrib hingga lepas Isya, kami semua akan sibuk mengaji, kemudian pulang ke rumah untuk nonton tivi sambil sesekali membuka buku karena ada PR dari guru.
Ritma Kehidupan yang Berubah karena Buku
Namun, ritma kehidupan itu agak berubah ketika tiba-tiba guru kelas, Bu Yati, menunjuk saya menjadi delegasi sekolah di tangkai lomba baca puisi. Belakangan saya tahu bahwa alasan beliau memilih saya bukan karena melihat potensi maupun bakat terpendam, tapi karena jarak rumah saya dan beliau hanya seperlemparan batu.
Tiap sore selepas Ashar saya sudah harus datang ke rumahnya untuk diajari bagaimana cara baca puisi yang baik. Namun, bukan itu satu-satunya hal yang saya ingat dari Bu Yati. Beliau dengan sangat berbaik hati meminjami saya majalah anak-anak milik cucunya. Saat itu saya merasa menjadi anak desa yang seberuntung anak-anak di kota. Gambar-gambar di majalah itu membuat imajinasi saya melampaui apa yang mampu saya pikirkan secara nyata. Percaya tidak percaya, setelah itu saya memelihara sebuah teman imajinatif di dalam diri. Saya senang ngobrol sendiri, menciptakan dialog-dialog bahkan adegan-adegan antara saya dan teman imaji itu.
Kebiasaan meminjam majalah itu berlangsung terus-menerus sampai pada suatu sore saya membawa serombongan teman untuk ikut meminjam majalah juga. Tapi, sungguh malang, majalah itu tidak pernah kembali lagi. Saya yang kena marah! Setelah sore itu, saya tidak pernah berani lagi meminjam majalah ke rumahnya. Tapi, ingatan saya tentang majalah-majalah itu sudah terlanjur lekat.
Menjadi Remaja yang (Kembali) Tidak Senang Membaca
Ketika duduk di bangku SMP, saya kembali menjadi manusia yang tidak senang membaca. Saya lebih menyenangi kegiatan fisik-motorik seperti ikut ekstrakurikuler drama dan pramuka. Lagi pula, perpustakaan di SMP saya keadaannya menyedihkan. Sejak saya sah menjadi siswa, gedung sekolah sedang dipugar besar-besaran.
Sayangnya, perpustakaan adalah tempat terakhir yang dipugar. Kami sudah terlanjur tidak mengenalnya. Sesekali saya membaca sastra di buku paket Bahasa Indonesia. Di sana saya mengenal nama Ahmad Tohari dengan sedikit biografinya. Saya betul-betul penasaran pada orang Banyumas yang mampu meraih banyak penghargaan dari menulis.
Saya berusaha mencari tahu di mana saya bisa meminjam buku itu. Sayang, Guru bahasa Indonesia saya pun tidak mengoleksinya. Belakangan, saya baru bisa membaca trilogi ‘Ronggeng Dukuh Paruk’ ketika duduk di bangku kuliah (S1). Rasanya seperti dendam yang harus terbalaskan, saya melahap habis triloginya kurang dari dua hari.[]