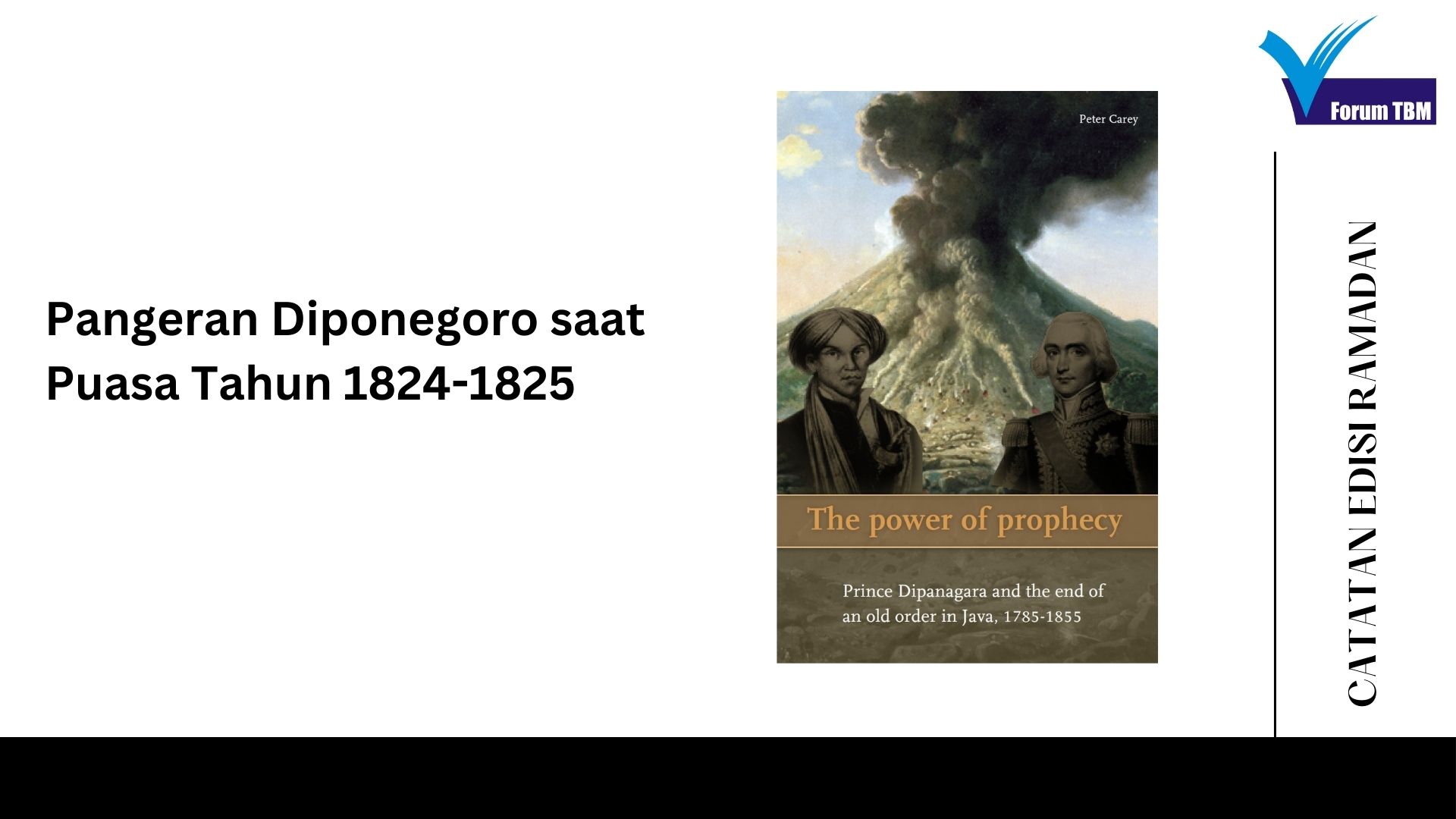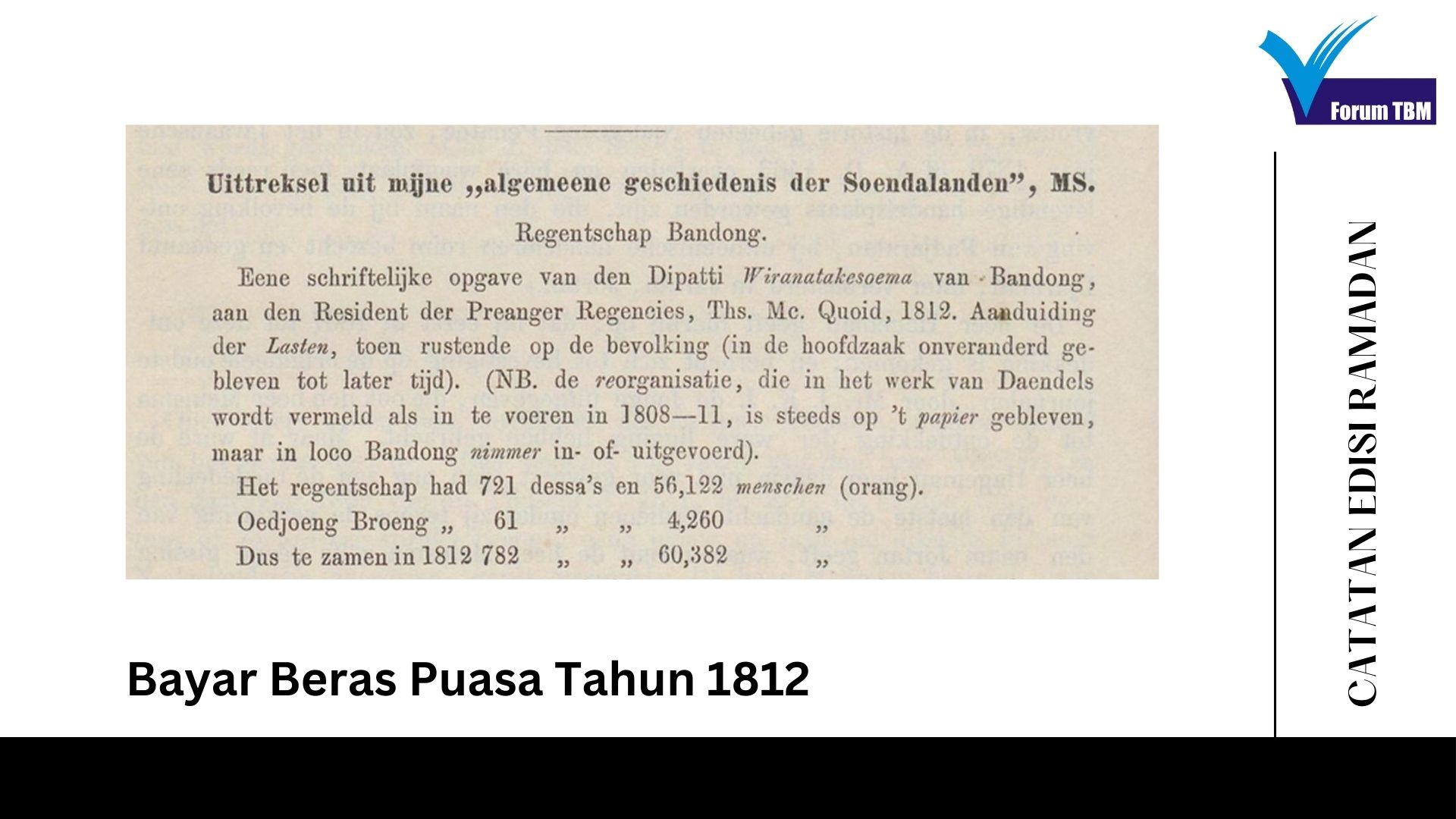Oleh. Darmawati Majid*
Dalam opininya di Harian Kompas, 7 Oktober 2022, Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, yakin bahwa dengan kerja keras dan gotong royong mewujudkan potensi besar menjadi kekuatan nyata, Indonesia akan berdiri di garis depan dalam pembanguan berkelanjutan berbasis kebudayaan untuk masa depan yang lebih baik. Pernyatan itu hasil mengikuti Konferensi Dunia UNESCO tentang Kebijakan Kebudayaan (Mondiacult) di Meksiko pada 28—30 September 2022. Konferensi yang menetapkan kebudayaan sebagai barang publik (seperti halnya pendidikan dan kesehatan) di tingkat global tersebut mengingatkan kembali mengenai peran penting kebudayaan dalam meningkatkan daya lenting masyarakat, memperkuat iklusi dan kohesi sosial, turut melindungi lingkungan hidup, dan memperkuat pembangunan yang berpusat pada manusia dan berakar pada konteks yang spesifik.
Kebetulan sekali opini tersebut dimuat Kompas enam hari setelah Tragedi Kanjuruhan, tragedi yang membuat nama Indonesia d(n)an Malang disorot berbagai media asing. Indonesia dikatakan telah menjadi bagian dari solusi global yang berpijak pada paradigma kolaborasi berkelanjutan yang mengedepankan manusia, bukan kepentingan sesaat. Dalam kaitannya dengan budaya menonton tim sepakbola andalan beramai-ramai sebagai bentuk dukungan, perihal “mengedepankan manusia dan bukan kepentingan sesaat” itu—kita saksikan—tidak diterapkan oleh pihak penanggung jawab.
Konon, negara mendukung ekonomi berbasis kebudayaan dan kreativitas melalui investasi, perangkat regulasi, dan penguatan kelembagaan, pada saat yang bersamaan, negara menjaga agar pemanfaaatan kekayaan budaya tersebut tidak berakhir menjadi komersialisasi berlebihan yang mereduksi ekspresi budaya jadi sekadar barang dagangan. Akan tetapi, apa yang kita saksikan di Kanjuruhan bertolak belakang dengan hal tersebut. Stadion yang kelebihan penonton jelas sebuah bentuk komersialisasi dan rapuhnya regulasi.
Dapat dikatakan bahwa tragedi Kanjuruhan sejatinya adalah efek domino dari kurangnya pendidikan literasi budaya dan kewargaan, serta literasi sains. Literasi budaya dan kewargaan, serta literasi sains merupakan dua dari enam komponen literasi dasar selain literasi baca-tulis, literasi numerasi, literasi digital, dan literasi finansial. Penguasaan keenam literasi dasar tersebut merupakan salah satu kompetensi abad ke-21 yang diperlukan semua warga dunia (Forum Ekonomi Dunia, 2015).
Literasi budaya dan kewargaan merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam menentukan sikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Kemampuan literasi ini akan mendorong sikap saling menghormati dan menghargai individu atau kelompok yang berbeda sehingga konflik antarpribadi dan antarkelompok dapat dihindari. Sementara itu, literasi sains menekankan pentingnya individu memiliki kepekaan terhadap kesehatan, sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan bencana alam dalam konteks personal, lokal, nasional, dan global. Literasi sains mengacu pada keterampilan seseorang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menggunakannya secara bijak terkait isu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kenegaraan. Literasi sains juga akan mengantisipasi pemanfaatan bahan-bahan kimia (seperti penggunaan gas air mata), dan produk-produk teknologi tanpa diimbangi dengan pemahaman dampak pemakaiannya terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan.
Literasi budaya dan kewargaan mencakupi enam prinsip, yaitu: 1) budaya sebagai alam pikir melalui bahasa dan perilaku; 2) kesenian sebagai produk budaya; 3) kewargaan multikultural dan partispatif; 4) nasionalisme, 5) inklusivitas; dan 6) pengalaman langsung, sementara itu literasi sains mencakupi lima prinsip: (1) kontekstual, sesuai dengan kearifan lokal dan perkembangan zaman; (2) pemenuhan kebutuhan sosial, budaya, dan kenegaraan; (3) sesuai dengan standar mutu pembelajaran yang sudah selaras dengan pembelajaran abad 21; (4) holistik dan terintegrasi dengan beragam literasi lainnya; dan (5) kolaboratif dan partisipatif.
Sebagai alam pikiran, budaya membawa bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahun, sistem religi, dan kesenian di dalamnya. Rahyono (2018) memaparkan dengan gamblang dalam bukunya yang berjudul Reaktualisasi Kecerdasan yang Terpinggirkan (WWS, 2018) bagaimana kebudayaan menggerakkan kehidupan manusia menjadi adil, beradab, dan bermartabat. Menurutnya, kebudayaan menjadikan manusia arif karena kebudayan tercipta berkat kecerdasan manusia, serta mampu menjadi sarana pencerdasan. Lalu, kebudayaan menjadikan kehidupan manusia beradab karena manusia mampu membuat tatanan sosial yang dipahami, dihayati, serta dimiliki bersama. Hou (2013) memiliki definisi berbeda: seperangkat ide dasar, praktik, dan pengalaman sekelompok orang yang secara simbolik diturunkan dari satu generasi ke generasi lain melalui proses pembelajaran. Jika benar demikian, manusia-manusia yang melakukan kekerasan di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu tentu bukan manusia yang berbudaya. Demikian halnya dengan para pihak yang seharusnya bertanggung jawab, yang kemudian memilih abai juga bukan bagian dari manusia-manusia yang arif, adil, beradab, dan bermartabat, juga cerdas sesuai apa yang dipaparkan Rahyono.
Penguatan literasi budaya dan kewargaan, serta literasi sains (empat literasi dasar lain) merupakan kerja yang belum selesai dan harus terus diupayakan. Kerja-kerja tersebut bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah dan komunitas literasi melainkan pula tanggung jawab pemangku kepentingan di negara ini dalam berpartisipasi menyukseskan Gerakan Literasi Nasional, sebagai kerja keras dan gotong-royong mewujudkan potensi besar Indonesia untuk berdiri di garis depan pembangunan berkelanjutan berbasis kebudayaan, demi masa depan bangsa yang lebih baik.
* Pengurus Pusat Forum Taman Bacaan Masyarakat